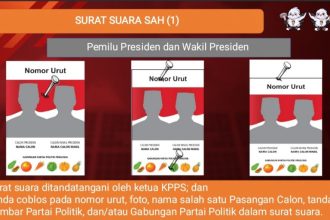Oleh: M. Azis Tunny
Tim Kerja Bidang Kajian Strategis dan Teritorial Pemilu BSNPG
Gagasan Kepala BSNPG (Badan Saksi Nasional Partai Golkar), Syahmud B. Ngabalin, untuk mengganti istilah “Hak Pilih” menjadi “Wajib Pilih” layak dipertimbangkan secara serius. Di tengah menurunnya partisipasi pemilih dalam berbagai pemilu belakangan ini, ajakan untuk menjadikan memilih sebagai kewajiban, bukan sekadar hak, adalah langkah strategis menuju demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat.
Selama ini, kita terbiasa menganggap pemilu sebagai ruang bebas. Warga boleh memilih, boleh juga tidak. Padahal, pemilu adalah mekanisme utama bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan. Ketika pemilu diabaikan, maka legitimasi pemimpin yang terpilih pun menjadi lemah. Di sinilah letak pentingnya menjadikan partisipasi sebagai kewajiban sipil, bukan pilihan sukarela.
Gagasan “wajib pilih” bukanlah hal asing. Negara-negara seperti Australia, Belgia, dan Brasil telah lebih dahulu menerapkannya. Hasilnya nyata, tingkat partisipasi pemilih di atas 90%. Bandingkan dengan Indonesia, yang pada pemilu 2019 dan 2024 masih menghadapi angka partisipasi yang fluktuatif, dengan banyak warga memilih golput karena apatis atau tidak merasa terikat secara moral untuk ikut memilih.
Menjadikan memilih sebagai kewajiban tidak lantas harus diikuti dengan sanksi pidana atau denda, melainkan lebih pada pembentukan budaya politik yang bertanggung jawab. Rakyat perlu didorong untuk sadar bahwa memilih bukan hanya soal menentukan pemimpin, tapi juga bentuk pertanggungjawaban terhadap masa depan bangsa.
Pemilu di Indonesia bukan proses murah. Biayanya mencapai triliunan rupiah dan menyerap sumber daya luar biasa besar. Jika rakyat tidak ikut serta, maka proses demokrasi ini menjadi pincang dan tak sebanding dengan investasi negara. Dalam konteks ini, dorongan Syahmud Ngabalin sangatlah relevan. Jika pemilu adalah ekspresi kedaulatan rakyat, maka setiap warga negara harus terlibat secara aktif dan sadar.
Tentu, pergeseran istilah dari “hak” ke “wajib” tidak cukup hanya secara semantik. Ia harus diikuti dengan edukasi politik yang masif, perbaikan sistem kepemiluan, dan kehadiran negara yang mampu memastikan akses memilih terbuka bagi semua. Namun langkah awal berupa perubahan cara pandang—bahwa memilih adalah kewajiban—adalah fondasi penting.
Demokrasi tak bisa berjalan hanya dengan segelintir orang yang peduli. Ia butuh partisipasi luas, kesadaran kolektif, dan keberanian untuk membangun tradisi baru dalam berdemokrasi. Dalam hal ini, gagasan Syahmud Ngabalin patut diapresiasi, bahkan ditindaklanjuti secara serius oleh penyelenggara pemilu, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil.
Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan pemilu sebagai acara lima tahunan yang bisa diabaikan. Memilih adalah tugas bersama. Demokrasi hanya akan bermartabat jika rakyatnya juga bertanggung jawab.